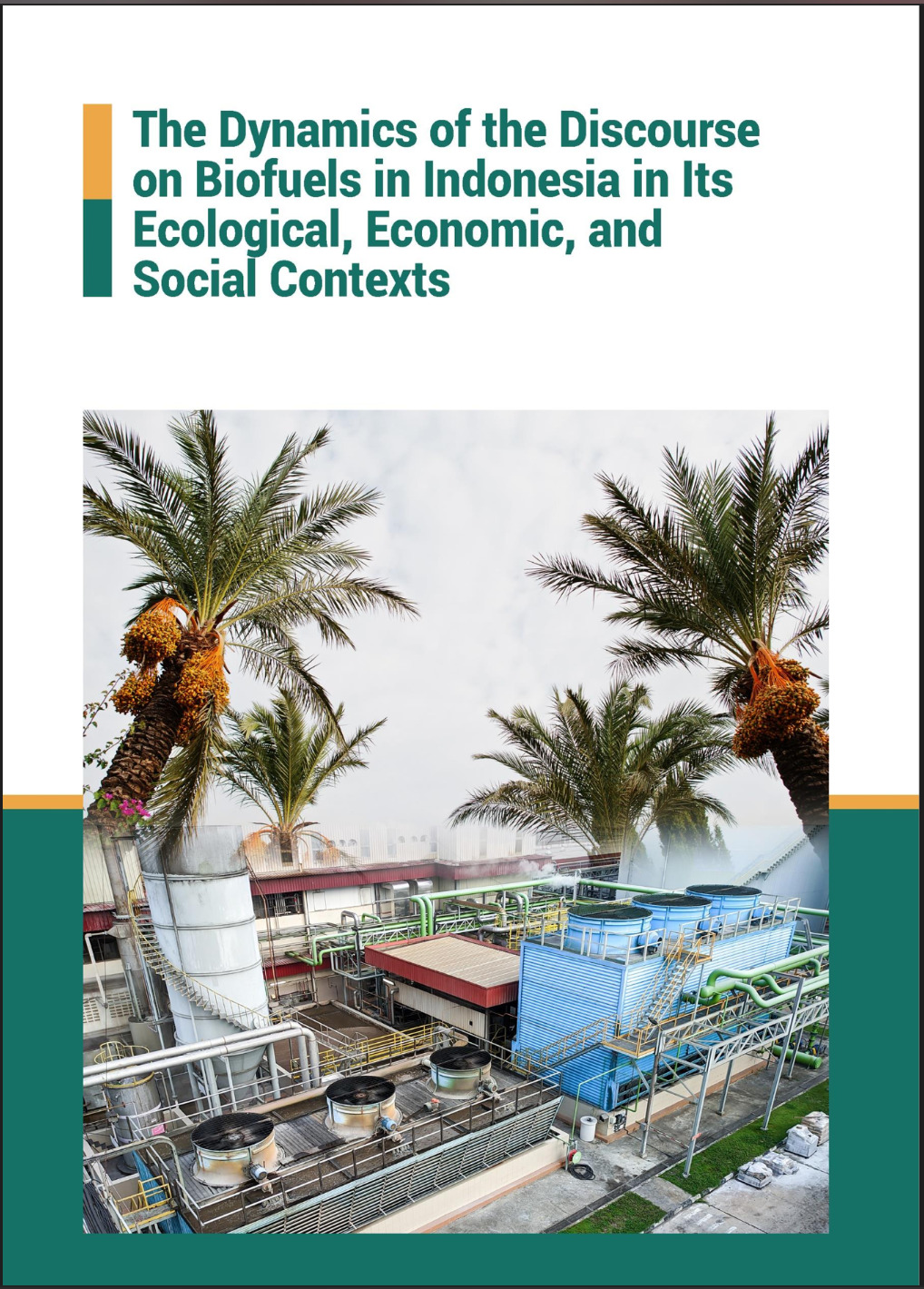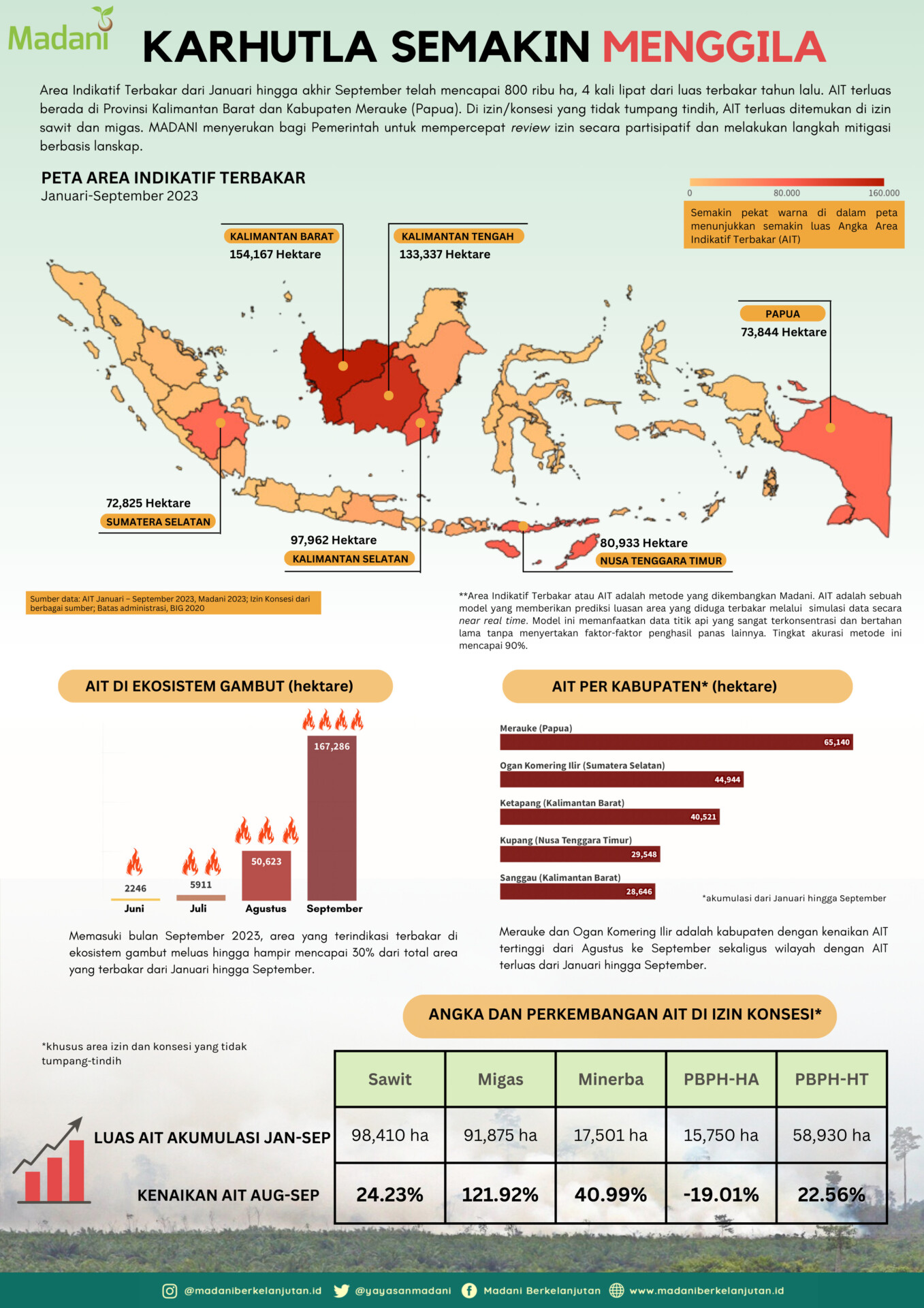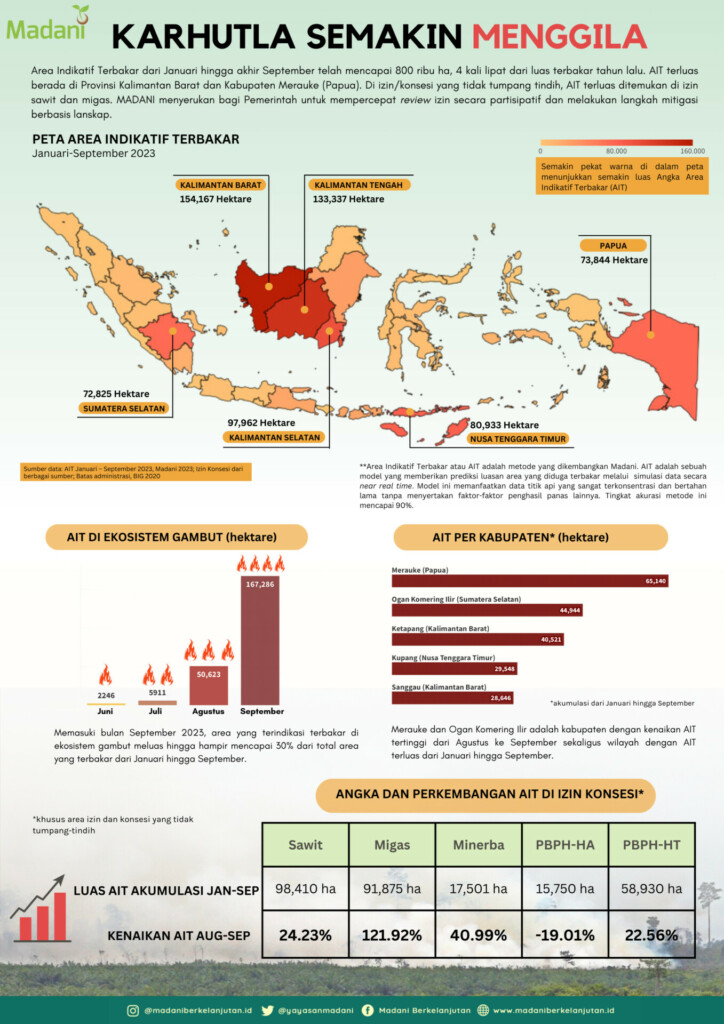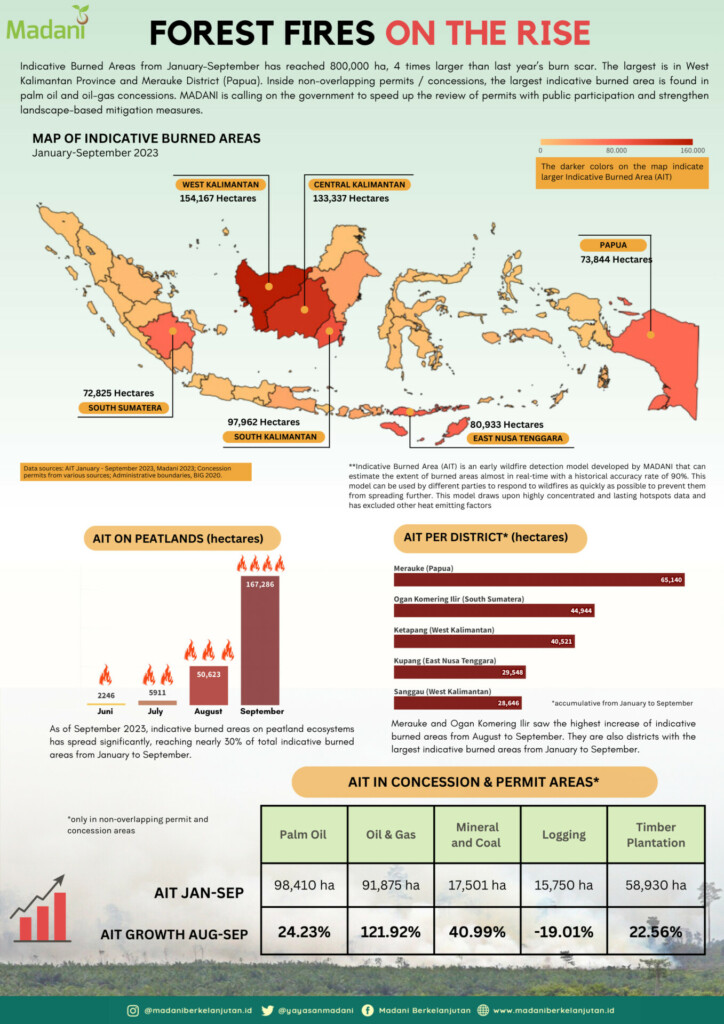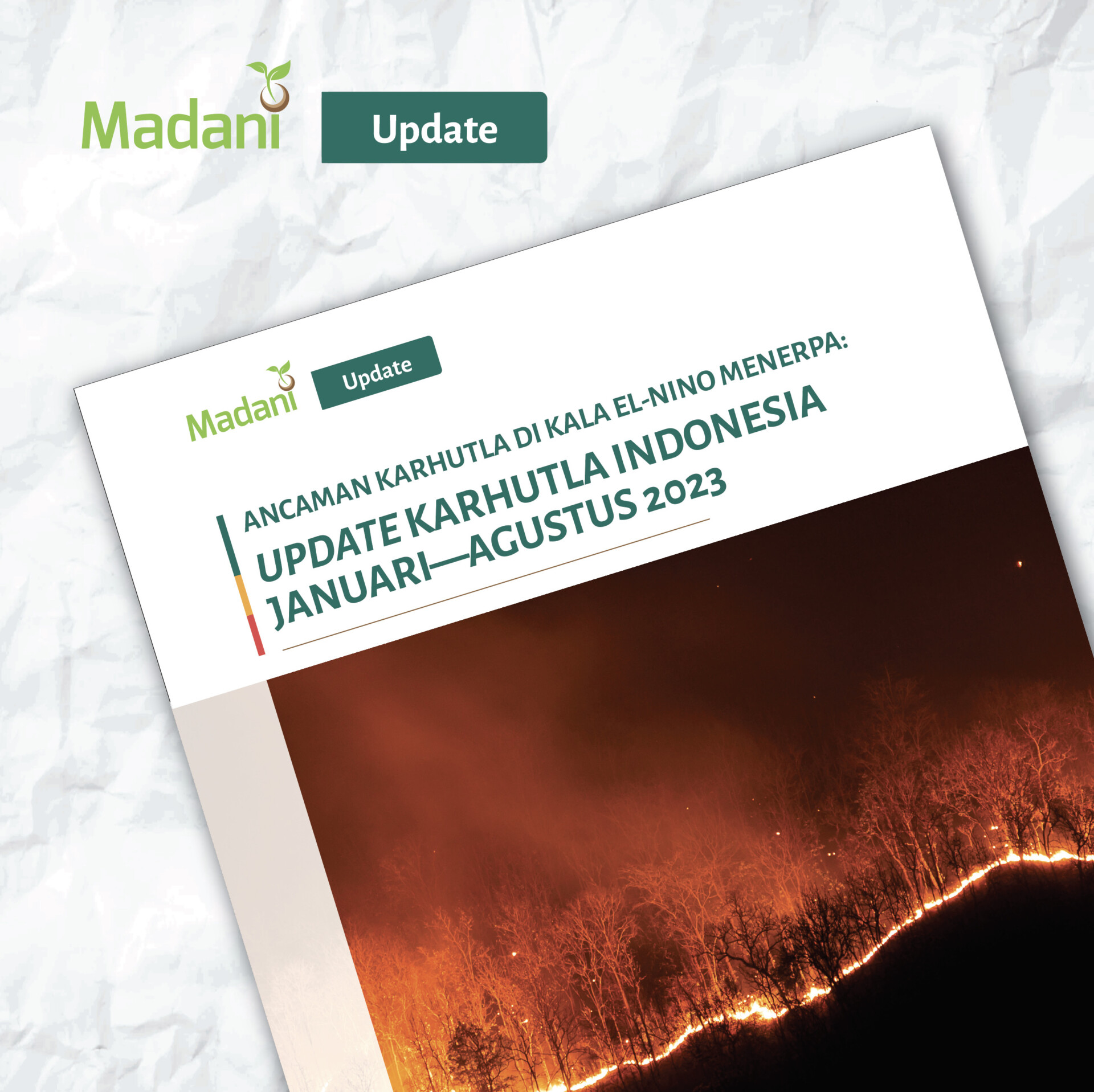[Siaran Pers] Jakarta, 26 September 2023. Tanpa perubahan sistemik, peluncuran bursa karbon yang ditandai dengan penunjukan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan dipandang berpotensi menjadi sarana mencari keuntungan semata tanpa berkontribusi pada penyelamatan umat manusia dari perubahan iklim. Demikian disampaikan oleh Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan menanggapi Peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
“Saat ini, suhu bumi sudah naik 1.1°C dan diperkirakan akan melampaui suhu 1.5°C pada awal dekade 2030. Dampak perubahan iklim sudah tidak terhindarkan. Oleh karenanya, tindakan mitigasi dan adaptasi secara simultan serta mendalam bukanlah pilihan melainkan sebuah tindakan wajib,” tambah Nadia Hadad.
“Indonesia sebagai negara kepulauan merasakan dampak signifikan dari krisis iklim, terutama pada masyarakat yang tergolong sebagai kelompok rentan seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, perempuan, masyarakat adat dan lokal, serta masyarakat yang berada di garis depan wilayah yang terdampak bencana iklim seperti kekeringan, banjir, angin ribut, naiknya permukaan air laut, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022), Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak 28.471 kejadian yang mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, 3,5 juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia. Bahkan Bappenas juga memprediksi kerugian ekonomi mencapai Rp. 544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim,” urai Nadia Hadad.
Perdagangan karbon adalah satu dari tiga mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021. Perdagangan karbon dapat dilakukan secara langsung maupun melalui bursa karbon. Ada dua jenis perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Dalam perdagangan emisi, pihak yang terlalu banyak mengeluarkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat membeli izin untuk mempolusi atau batas atas emisi GRK (PTBAU-PU). Dalam skema offset, pihak yang mengeluarkan emisi GRK dapat mengkompensasi emisi yang dikeluarkannya dengan membeli kredit offset (SPE-GRK).
Sementara itu, Giorgio Budi Indrarto, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, memaparkan bahwa ada tujuh poin yang harus diperhatikan agar perdagangan karbon tidak menjadi praktik pencitraan atau greenwashing. “Yang pertama, semua negara, termasuk Indonesia, harus meningkatkan ambisi kontribusi nasionalnya (NDC) agar selaras dengan jalan menuju 1,5 derajat Celcius dan menyelaraskan kebijakan-kebijakan pembangunan dalam negeri di seluruh sektor dengan komitmen iklim tersebut. Kedua, perlu ada penetapan batas atas emisi GRK yang ketat dan transparan. Saat ini, baru PLTU yang dikenai batas atas emisi. Penetapan kewajiban pengurangan emisi GRK kepada Pelaku Usaha di sektor kehutanan juga perlu dipertegas karena Pelaku Usaha menguasai hutan dan lahan dalam jumlah besar.”
“Ketiga, offset harus dibatasi hanya untuk emisi residual, yaitu emisi yang masih tersisa setelah pencemar melakukan aksi penurunan emisi GRK secara optimal. Tanpa pembatasan ini, skema offset justru berisiko menjadi insentif yang sesat jalan, yang dapat menghambat pelaksanaan aksi mitigasi yang ambisius. Keempat, aturan perdagangan karbon perlu memastikan integritas sosial dan lingkungan, termasuk nilai tambah (additionality), keterandalan (reliability), dan kelestarian (permanence). Mengkompensasi emisi di sektor energi dengan kredit offset dari sektor hutan dan lahan perlu dihindari karena berbagai masalah terkait integritas yang belum terselesaikan. Pengaturan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang diserahkan pada berbagai standar nasional dan internasional yang ada juga perlu diperjelas,” tambah Giorgio Budi Indarto.
Kerangka aturan perdagangan karbon kehutanan juga harus mendorong kebijakan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan hutan dan lahan yang jadi penghambat utama partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal, mempercepat realisasi perhutanan sosial dan reforma agraria sejati, memprioritaskan hutan untuk masyarakat tak bertanah ketika terjadi konflik klaim dengan perusahaan, serta mengembangkan standar publik untuk mengembangkan aset karbon yang absah secara ilmiah dan dapat diakses cuma-cuma oleh komunitas penjaga hutan.
Pemerintah juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan rantai perdagangan karbon, mulai dari penyusunan peta jalan perdagangan karbon, perizinan proyek karbon, pengalokasian batas atas emisi, hingga penyelenggaraan bursa karbon itu sendiri, termasuk dengan mencegah praktik-praktik yang mengarah pada spekulasi dan manipulasi pasar karbon, serta potensi konflik kepentingan regulator atau para pihak terkait lainnya.
Terakhir, mengingat hutan dan ekosistem itu sendiri sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, membangun ketahanan atau resiliensi ekosistem dan masyarakat menjadi sangat penting. Untuk itu, Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen untuk mencapai target NDC dan mengendalikan emisi GRK perlu memastikan pendanaan yang memadai untuk adaptasi perubahan iklim yang efektif dan berkeadilan. Tanpa pemenuhan berbagai prakondisi dan persyaratan di atas, akan sangat sulit bagi perdagangan karbon untuk menjadi bagian dari perwujudan keadilan iklim.
Keadilan iklim adalah prinsip penting di tengah ketidakadilan lingkungan dan ekologis, yang polanya dapat dikenali dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh ekstraksi, perusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengabaian hak asasi manusia, serta melepaskan emisi gas rumah kaca. Dampaknya adalah ketidakadilan, ketidakmerataan, kemiskinan, dan menurunnya kemampuan warga untuk bertahan dan kehilangan sumber penghidupan serta ruang hidup yang sehat.
Bentuk dan pola ketidakadilan iklim ini pada akhirnya menurunkan kemampuan lingkungan dan masyarakat untuk dapat bertahan dan mengatasi dampak krisis iklim. Dengan demikian, semua upaya intervensi mitigasi maupun adaptasi krisis iklim harus mengadopsi azas keadilan sebagai prinsip aplikatif utama, termasuk implementasi dan tata kelola Bursa Karbon.
[ ]
***
Manusia dan Alam untuk Indonesia (MADANI) Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Didirikan pada 2016, MADANI Berkelanjutan berupaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak. Saat ini, fokus kerja MADANI Berkelanjutan meliputi isu hutan dan iklim, komoditas berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah, dan biofuel.